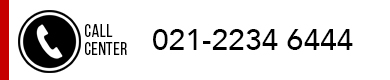- Detail
- Dilihat: 57086
 Jakarta - Tayangan Infotainment tentang perseteruan saling tantang adu tinju antara Farhat Abbas dengan Ahmad Al Ghazali (Al) dan El Jalaluddin Rumi (El) sedemikian mendominasi semua stasiun televisi nasional beberapa pekan terakhir. Bagi industri televisi (lembaga penyiaran), tayangan konfliktual dunia selebritas semacam ini menjadi lahan potensial kian meningkatkan rating/share untuk keuntungan finansial melalui iklan.
Jakarta - Tayangan Infotainment tentang perseteruan saling tantang adu tinju antara Farhat Abbas dengan Ahmad Al Ghazali (Al) dan El Jalaluddin Rumi (El) sedemikian mendominasi semua stasiun televisi nasional beberapa pekan terakhir. Bagi industri televisi (lembaga penyiaran), tayangan konfliktual dunia selebritas semacam ini menjadi lahan potensial kian meningkatkan rating/share untuk keuntungan finansial melalui iklan.
Agar tetap menyedot perhatian publik (rating tinggi), kasus ini dieksploitasi melalui dramatisasi sound effect, editing gambar dan presenter provokatif. Bahkan bila perlu, masalah diperuncing secara emosional melalui pelibatan keluarga, saudara dan tetangga sang artis. Tayangan konflik antara Farhat versus dua anak musisi Ahmad Dhani ini hanyalah satu dari ribuan kasus selebritis di layar kaca pemirsa yang kerap didramatisasi. Inilah sejatinya anatomi infotainment terhidang di ruang keluarga Indonesia.
Problem Jurnalisme
Dalam disiplin ilmu jurnalisme, terjadi perdebatan panjang tanpa titik temu mengenai: apakah infotainment merupakan produk jurnalistik ataukah bukan? Di satu pihak dinyatakan bahwa infotainment adalah produk jurnalistik, mengingat pemberitaan artis masih berbasis pada metode dan teknik jurnalistik seperti reportase, pengusungan 5W dan 1H, dan kaidah cover both sides.
Di pihak lain dinyatakan infotainment bukan produk jurnalistik karena didasarkan pada gosip. Meski dalam berbagai domain meliputi unsur aktualitas, namun pemberitaan tentang dunia artis ini dipenuhi dramatisasi peristiwa dan pendasaran fakta pada aspek ‘jikalau’ (if), sehingga ia kerapkali mengangkat unsur ‘syakwasangka’. Di domain produksi, beberapa program infotainment masih diproduksi oleh production house (penyedia konten) dengan kru lapangan yang kerap tak dibekali kepiawaian jurnalisme. Terlebih, penghormatan terhadap hak privasi pada Pasal 2 poin b dalam Kode Etik Jurnalistik kerap dilanggar.
Terlepas pro-kontra diatas, kasus perseteruan Farhat versus Al-El memunculkan masalah kode etik, bahwa El sebagai anak dibawah umur tak patut menjadi narasumber bagi konflik orang tuanya. Hal ini bertentangan pula dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sebagai aturan baku untuk program siaran televisi.
Perspektif Dampak
Tayangan infotainment nyata berdampak besar bagi perkembangan psikologis masyarakat dan memengaruhi karakter kebangsaan kita. Sebab artis merupakan figur publik dengan daya tarik besar (great seduction) untuk kemungkinan diikuti oleh mayoritas muda-mudi dan kaum hawa lainnya dari segala umur. Artis adalah pusat trend (trend setter) yang akan terus diimitasi dan diadopsi pola kehidupan mereka oleh khalayak pemirsa. Tak hanya dari segi busana, penampilan dan gaya hidup, bahkan pula sikap dan perilaku sehari-hari. Ia secara fulgar dieksploitasi di ruang publik melalui infotainment dan program hiburan lainnya. Dalam jangka panjang, jika tayangan infotainment masih menyajikan beragam konflik pribadi seputar pertengkaran antar selebritis, perceraian dan rebutan anak, ribut soal harta goni-gini, maka lambat laun bias jadi mentalitas puluhan juta pemirsa terdegradasi.
Meski pemirsa kian kritis, namun daya injeksi infotainment jauh lebih kuat, menegaskan keabsahan dalil sosiolog Perancis, Jean Baudrillard dalam In The Shadow of Silent Majorities (Columbia University: 1983). Ia mengungkap televisi sebagai pencipta model acuan nilai dan makna sosial budaya masyarakat dewasa ini, melalui telenovela, iklan, film, dan gaya hidup selebritis (infotainment). Bagi Baudrillard, pemirsa adalah “mayoritas yang diam” (the silent majorities), pasif menerima segala tayangan ke dalam pikiran dan perilaku, menelannya mentah-mentah tanpa pernah mampu merefleksikan kembali dalam kehidupan nyata, dan bahkan hanyut dalam gelombang deras budaya massa dan budaya populer.
Merujuk fenomena ini, agar tayangan infotainment lebih berdampak konstruktif, peningkatan kualitas tayangan dapat dilakukan melalui empat hal. Pertama, terkait tayangan konflik artis, infotainment semestinya menggunakan metode jurnalisme damai, bukan jurnalisme konflik. Artinya orientasi pemberitaan konflik artis niscaya digeser. Bukan kian memperuncing dan memperpanas, sebaliknya berperan sebagai peredam dan mediator rekonsiliasi konflik selebritis.
Kedua, menghindari tayangan ber-angle konflik pribadi semacam pertengkaran antar artis, diganti dengan tayangan bernuansa edukatif lain seperti agenda programatik artis dan kegiatan positif lain. Konteks ini, muncul kekhawatiran apabila tidak mengupas konflik, rating/share akan turun. Dan jika rating/share turun, harga dan jumlah iklan pun turun. Justru disinilah akar masalahnya. Rating/share sudah terlanjur menjadi ‘dewa’ bagi program televisi secara keseluruhan, tak terkecuali infotainment. Parahnya, diantara faktor utama pendongkrak rating/share adalah jualan konflik, dan para pengiklan mengamini. Mata rantai ini mesti diputus dan paradigma harus digeser, bahwa rating/share bukanlah satu-satunya tools, tetapi tayangan sehat, berkualitas dan edukatif musti dijadikan umpan utama mengail iklan.
Ketiga, berkait masalah diatas, ‘suara hati’ semua pihak musti terbuka. Pekerja media, pengiklan dan terkhusus bagi pemilik media tak selayaknya hanya mengejar rating semata namun melupakan pendidikan karakter bangsa. Naif bila pemasangan iklan diarus-utamakan pada rating tinggi, namun berdampak merusak moral bangsa. Kaitan ini, suara hati pengiklan mestinya terketuk dengan tidak memasang iklan pada program yang terkena teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perihal pelanggaran P3SPS.
Keempat, penguatan kapasitas praktisi infotainment. reporter, kameramen, produser, penulis naskah dan editor (news room) semestinya dibekali kapasitas jurnalistik memadai dan memahami aturan dalam P3SPS agar mampu meningkatkan kualitas tayangan, baik bagi production house selaku penyedia konten maupun terhadap kru inhouse production lembaga penyiaran. Bila perlu, semua program infotainment dikelola secara inhouse oleh divisi news. Atas dasar kebutuhan penguatan kapasitas jurnalisme dan pemahaman P3SPS, dibutuhkan uji kompetensi pekerja media secara selektif, ketat dan berkala sebagai lisensi (syarat masuk) menjadi pekerja media di lembaga penyiaran, sebagaimana kini digagas oleh Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
KPI telah melayangkan surat edaran ke lembaga penyiaran agar tayangan konflik antara Farhat dengan Al dan El segera dihentikan. Banyak aspek pelanggaran P3SPS, baik aspek penghormatan terhadap hak privasi maupun perlindungan kepada anak.
Akhirnya, agar program infotainment tak mendegradasi perilaku dan mentalitas jutaan pemirsa di seluruh pelosok negeri ini, semua pihak, terutama lembaga penyiaran harus menyadari posisi dan tanggungjawabnya dalam memperkuat karakter kebangsaan melalui tayangan sehat dan edukatif.
Danang Sangga Buwana
Komisioner KPI Pusat
Artikel dari Oke Zone


 (Danang Sangga Buana) Industrialisasi Politik di Layar Kaca
(Danang Sangga Buana) Industrialisasi Politik di Layar Kaca Jakarta – Dalam satu kunjungan ke FCC (Federal Comunication Comission) 18 – 21 April 2013 lalu di AS, Koordinator bidang Perizinan sekaligus Komisioner KPI Pusat, Iswandi Syahputra dan Komisioner KPI Pusat, Judhariksawan, mendapatkan beberapa pengalaman berharga. Dari beberapa pertemuan mereka dengan perwakilan FCC, sejumlah materi berikut presentasi seputar siaran digital disampaikan pihak FCC kepada kedua Komisioner tersebut.
Jakarta – Dalam satu kunjungan ke FCC (Federal Comunication Comission) 18 – 21 April 2013 lalu di AS, Koordinator bidang Perizinan sekaligus Komisioner KPI Pusat, Iswandi Syahputra dan Komisioner KPI Pusat, Judhariksawan, mendapatkan beberapa pengalaman berharga. Dari beberapa pertemuan mereka dengan perwakilan FCC, sejumlah materi berikut presentasi seputar siaran digital disampaikan pihak FCC kepada kedua Komisioner tersebut.